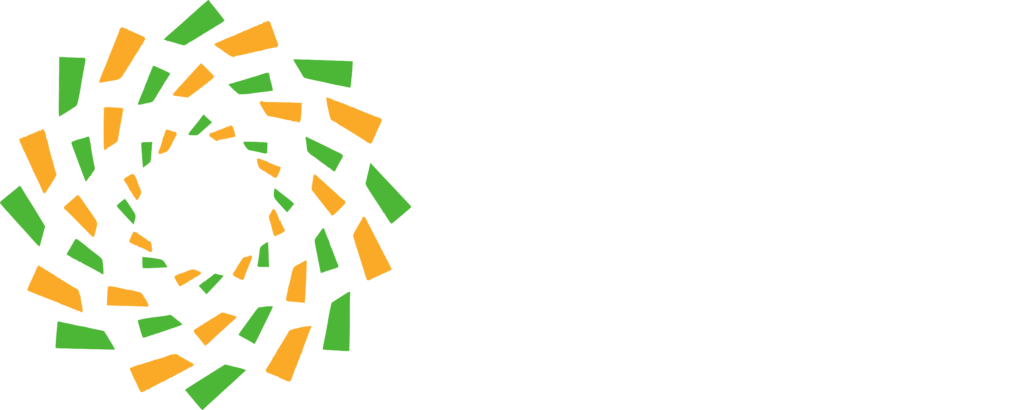Kartini, Sebuah Renungan

Kartini adalah pembuat kisah. Sebuah kisah tentang pemikiran dan perjungan hidup. Kartini adalah sebuah identitas naratif yang menginspirasi banyak orang. Karena itu, kisah Kartini, pinjam istilah filsuf Paul Ricoeur, tidak berdiri sendiri. Kisah itu bertaut dengan kisah-kisah lain yang muncul sebelum, semasa, dan sesudah Kartini hidup. Itulah sebabnya, kisah hidup Kartini sangat inspiratif dan tidak lekang oleh zaman. Dan kini, karena kisah-kisah hidup dan perjuangannya, Kartini telah berubah menjadi sejarah. Kartini adalah sejarah itu sendiri.
Tak mudah memang memahami sejarah kepahlawanan Kartini. Bahkan seorang sejarawan terkenal, Prof. Dr. Harsja Bachtiar, pernah menggugatnya. Tulis Harsja, Kartini adalah kisah pahlawan yang dibesarkan Belanda. Harsja menilai, kepahlawanan Kartini dimunculkan karena surat-surat yang dikirimnya kepada orang-orang Belanda, yang nota bene teman-teman Kartini dan mereka penjajah. Harsya tampaknya lupa, pada masanya hidup seorang perempuan seperti Kartini sangat sulit. Belenggu tradisi dan adat priyayi, menutup semua akses untuk wanita yang ingin keluar dari kepungan budaya feodalisme.
Melalui surat-suratnya itulah, Si Trinil – panggilan akrab putri Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, Bupati Jepara ini – memberontak. Sebagai gadis Jawa yang ingin menguak dunia, Kartini memberikan inspirasi, bagaimana seharusnya wanita itu hidup. Wanita harus berpendidikan, kata Kartini, karena wanita-lah yang akan mendidik generasi. Tidak persoalan apakah wanita terdidik itu kelak hanya menjadi ibu rumah tangga atau hidup di bawah kungkungan tradisi feodalisme; yang jelas kaum wanita terdidik akan bisa membesarkan anak-anaknya dengan cara yang lebih baik dan educated untuk merubah masa depannya. Wanita-wanita terdidik, meski hanya ibu rumah tangga, tetap akan memberikan pencerahan dan inspirasi kepada keluarga sehingga keluarga itu akan maju. Dan itulah yang diinginkan Kartini.
Awalnya Kartini kalah. Si Trinil “dipaksa” secara tradisi menikah dengan pria pilihan ayahnya, Bupati Rembang K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat. Ia tak bisa menolak. Tapi Kartini tetap ingin memperjuangkan idealismenya. Kesempatan menjadi raden ayu yang terhormat di mata perempuan Jawa, ia manfaatkan untuk mendidik ibu-ibu di sekitar rumahnya, membangun sekolah untuk anak-anak perempuan, dan terus menyadarkan kaumnya agar keluar dari kegelapan.
Lihat salah satu surat Kartini yang ditulis 6 November 1899 untuk temannya, Stella Zeehandelaar. Trinil menulis: “Jalan kehidupan gadis Jawa itu sudah dibatasi dan diatur menurut pola tertentu. Kami tidak boleh mempunyai cita-cita. Satu-satunya impian yang boleh kami kandung ialah, hari ini atau besok dijadikan istri yang kesekian dari seorang pria. Saya tantang siapa yang dapat membantah ini. Dalam masyarakat Jawa persetujuan pihak wanita tidak perlu. Ia juga tidak perlu hadir pada upacara akad nikah. Ayahku misalnya bisa saja hari ini memberi tahu padaku: Kau sudah kawin dengan si anu. Lalu aku harus ikut saja dengan suamiku. Atau aku juga bisa menolak, tetapi itu malahan memberi hak kepada suamiku untuk mengikat aku seumur hidup tanpa sesuatu kewajiban lagi terhadap aku. Aku akan tetap istrinya, juga jika aku tidak mau ikut. Jika ia tidak mau menceraikan aku, aku terikat kepadanya seumur hidup. Sedang ia sendiri bebas untuk berbuat apa saja terhadap aku. Ia boleh mengambil beberapa istri lagi jika ia mau tanpa menanyakan pendapatku. Dapatkah keadaan seperti ini dipertahankan, Stella?”