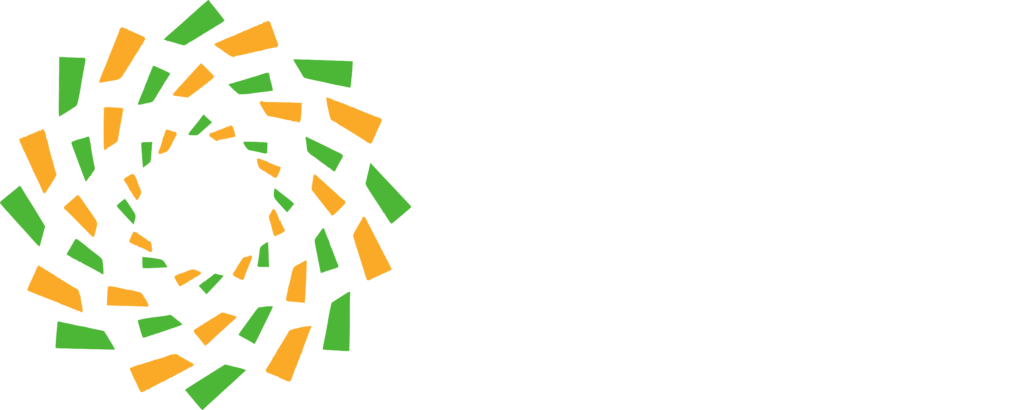Apa Itu Kebahagiaan

Oleh : Haidar Bagir
Rasanya, tak ada satupun makhluk manusia yang tidak sependapat bahwa tujuan hidup manusia di muka bumi ini adalah mencapai kebahagiaan (happiness, sa’adah). Meski kebahagiaan bisa dipahami dalam berbagai bentuknya – ada yang melihatnya sebagai bersifat psikologis, ada yang intelektual, dan ada yang spiritual-semua sepakat pada sifatnya yang menjadikan manusia merasa bukan hanya bergairah, bersemangat, dan menikmati hidupnya, melainkan terutama menebarkan ketentraman, kedamaian, kepenuhan makna, dan kepuasan yang tak menyisakan kekosongan. Sementara, penderitaan (misery,syaqawah) sama dengan kegelisahan, kekacauan, kehampaan makna, dan kekuranganyang menganga.
Perlu segera disusul, kebahagiaan tidak sama dengan kumpulan kenikmatan (pleasure). Mungkin saja hidup seorang dipenuhi kenikmatan, tetapi dia tidak bahagia. Kebahagiaan juga bukan berarti ketiadaan kesulitan atau penderitaan. Karena, boleh jadi penderitaan dating silih berganti, tetapi kesemuanya itu tak merusak keberadaan kebahagiaan. Inilah yang disebut sebagai underlying happiness kebahagiaan yang senantiasa melambari) hidup kita.
Perlu dipahami juga, kebahagiaan tak sama dengan kenikmatan sesaat, tapi jaminan bahwa kenikmatan itu tak akan segera berganti dengan perasaan hampa, tanpa kebebasan dari kegelisahan terhadap prospek kehampaan dimsa setelah itu. Dengan demikian, kenikmatan itu tak pernah betul-betul tertanam di dasar hati kita, melambari segala pancaroba kejadian yang mungkin berlangsung di sekitar hidup kita, sehingga ia terasa sebagai sekedar sesuatu yang mengembang di kedangkalan permukaan hidup kita. Begitu juga sebaliknya.
Dilihat (dirasakan) melalui fondamen underlying happiness, apa saja yang terjadi di permukaan hidup kita akan masuk ke hati sebagai sesuatu yang memberi makna positif kepada diri kita, menentramkan, dan membahagiakan. Dapat saja saat ini kita sedang tertimpa kesulitan dan kesedihan, tetapi keyakinan bahwa kehidupan bersifat baik, positif, dan mensejahterakan tak akan terganggu karenanya. Kebahagiaan mempberikan bayangan kedamaian dan ketentraman yang lebih lestari. Ini sebabnya, sebagian orang mengidentikkan kebahagiaan dengan “kebaikan – kebaikan yang lestari” (al-baqiyat al-shalihat) sebagaimana difirmankan- Nya :
Harta dan anak – anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Namun, kebaikan – kebaikan yang lestari adalah lebih besar ganjarannya di sisi Tuhanmu dan lebih layak dijadikan harapan. (QS AL – Kahfi [18]: 46)
Memang, kebahagiaan tidak bersifat fisikal, bahkan tidak psikologis – jika psyche dipahami secara dangkal sebagai kumpulan gejala yang semata – mata bersifat conscious – serebal belaka. Kebahagiaan sepenuhnya bersifat spiritual – meski tak mesti selalu sama dengan hal – hal yang bersifat keagamaan – formal – yakni terkait dengan hati. Spiritual adalah suatu daya dalam diri manusia yang bukan hanya lebih tinggi dari daya intelektual serebral, melainkan juga melampaui emosi dan perasaan yang – betapa pun terkait dengan hati – masih belum lagi mengatasi ketidakstabilannya, yang unsur-unsurnya belum lagi terkombinasi dalam jumlah dan ukuran yang seimbang, yang stabil. Memang emosi dan perasaan memiliki semua unsure untuk stabil dan mendatangkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, tetapi tak selalu kombinasinya terjadi dalam ukuran yang seimbang.
Nah, terhadap emosi yang seimbang ini, tak ada satu pun kejadian di luar hati kita yang akan mampu mengusik keseimbangan yang sudah tercapai itu, yakni kebahagiaan yang melambari ini. Tak ada suka cita yang terungkap di luar kendali sehingga dapat memukul balik dan membuka kemungkinan bagi kesengsaraan setelahnya, tak pula ada kesedihan yang terlalu besar sehingga dapat mengoyak fondamen kebahagiaan kita. Tak ada kejadian apa pun dalam pancaroba kehidupan yang dapat memberikan pengaruh yang terlalu dalam sehingga mengusik kebahagian kita. Persis sebagaimana batu yang dilempar ke air yang dangkal akan menghasilkan riak yang besar, sementara benda yang sama di laut dalam tak akan merusak ketenangan permukaan.
Memang kebahagiaan bersifat intrinsik, ada di dalam hati kita, bukan ekstrinsik dan tergantung pada pancaroba kejadian dalam kehidupan sehari – hari kita di luarnya. Bagi yang telah meraih kebahagiaan – yang melambari ini, apa pun bisa terjadi dalam kehidupan “ luaran” kita, tetapi rasa kebahagiaan akan tetap lestari. Bagi orang – orang yang memilikinya, kenikmatan dan kesulitan bersifat sepenuhnya relatif. Keduanya tak memiliki makan independennya sendiri. Relatif terhadap underlying happiness ini, sesungguhnya tak ada kesulitan. Begitu tertempatkan di lambaran atau fondamen kebahagiaan ini, semuanya menjadi unsure yang membahagiakan. Kenikmatan dan kesedihan oun menjadi terbatas pada penampakan – luar atau kemasan. Pada hakikatnya dia selalu bermakna sebagai unsur kebahagiaan. Inilah, yang secara popular , membuat banyak orang menyatakan : pada puncaknya kebahagiaan (dan kesengsaraan) sesungguhnya produk persepsi. Apa saja, jika ia persepsikan secara positif, akan menyumbang kepada kebahagiaan kita, meskipun penampakan luar atau kemasannya lebih menyerupai kesulitan. Sebaliknya, jika kita persepsikan secara negatif, apa saja akan melahirkan kesengsaraan, meski penampakan luar atau kemasannya indah.
Bahkan, dapat kita katakana bahwa sesungguhnya kesedihan adalah sesuatu yang niscaya agar kita dapat mengidentifikasi dan merasakan kebahagiaan. Orang yang tak pernah merasakan kesedihan atau kesusahan akan kebal atau tidak sensitive terhadap kebahagiaan. Sekedar kesusahan justru dapat menjadi latar belakang yang di atasnya kita benar – benar dapat merasakan dan mengapresiasi kebahagiaan. Sayyidina ‘Ali karamllaha wajhah pernah mengatakan, “ Seseorang tidak akan merasakan manisnya kebahagiaan (sa’adah), sebelum dia merasakan pahitnya kesedihan (syaqawah).” Mungkin bukan tidak pada tempatnya kita jernihkan di sini bahwa, meski syaqawah sering dianggap lawan kata dari sa’adah dan kata – kata lain yang mengungkapkan kebahagiaan, ia tak pernah boleh diartikan sebagai memilki kemungkinan keabadian sebagaiman sa’adah. kasih sayang Allah sedemikian tak terbatas sehingga menutup kemungkinan bagi syaqawah atau kesengsaraan yang abadi. Betapa pun, syaqawah selalu harius dilihat sebagai pendahulu bagi sa’adah. dengan kata lain, sa’adah adalah prinsip kehidupan manusia, sedang syaqawah adalah pengecualian. Syaqawah diperlukan sekedar tolak ukur, yang melaluinya orang bisa mengidentifikasi dan mengapresiasi kebahagiaan. Paling tidak, syaqawah juga hanya bisa dilihat sebagai sarana Allah mengajar dan member pelajaran kepada kita agar terdorong untuk menjadi lebih baik.
Pada kenyataannya, bahkan mereka pun harus dilihat dengan cara demikian. Seperti dapat kita lihat dalam berbagai ayat Al – Quran, selain melihat siksaan di neraka sebagai alat pendidikan untuk menyucikan jiwa manusia yang kotor, Allah selalu membuka kemungkinan bagi tidak abadinya siksaan di neraka. Ayat di bawah ini adalah salah satu contohnya :
Maka, orang –orang yang sengsara (menyandang syaqawah) itu, mereka kekal di dalam neraka selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki … (QS Hud [11]: 107)
Kenyataannya, bukan saja langit dan bumi tidak abadi, bahkan – seperti, dinyatakan oleh Ibn ‘Arabi – kata ganti milik “ha” dalam ungkapan “khalidina fi ha” kembalinya kepada neraka, bukan kepada siksa. Menurut ‘urafa’ seperti ini, boleh jadi neraka akan abadi, tetapi siksaanya tidak. Demikian pula halnya dengan syaqawah.
sumber : Buku Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan