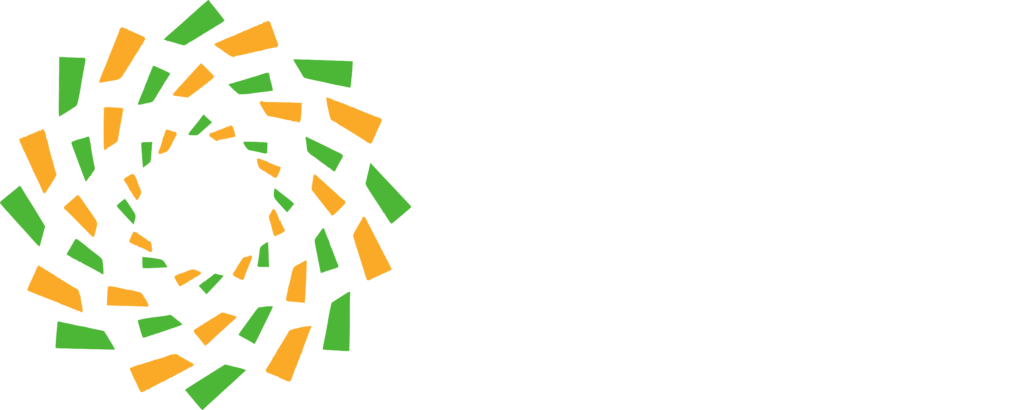Mindset Korupsi dan Pemerataan Pendidikan

Sekali-kali, berjalan-jalanlah ke kampung-kampung dekat pelabuhan ikan Pelabuhan Ratu. Lalu, amati anak-anak usia sekolah SMP. Ternyata banyak sekali yang tidak sekolah. Mereka memilih bekerja. Ada yang di pelabuhan ikan, ke kota jadi pedagang asongan, atau ke Jakarta jadi tukang parkir dan penyemir sepatu.
Mereka, ternyata bukan anak orang miskin. Orang tuanya secara ekonomi lumayan. Ini terlihat dari rumahnya yang relatif bagus. Bertembok, pakai keramik, dan ada tivi. Tapi kenapa anak-anaknya tidak disekolahkan ke SMP?
Ternyata, orang tua mereka menganggap sekolah itu menghabiskan waktu dan uang. Mendingan kerja, anak-anak bisa mendapatkan uang. Pikiran itu pun direspons positif anak-anak. Sinergi pikiran orang tua dan anak itu menghasilkan kesimpulan: lebih baik tidak sekolah tapi bisa menghasilkan uang ketimbang sekolah menghabiskan uang. Dalam kasus ini, sekolah dan tidak sekolah adalah persoalan mindset! Itu yang terjadi di desa-desa sekitar Pelabuhan Ratu, Sukabumi.
Tapi bagaimana dengan desa-desa sekitar Jakarta? Ambil contoh di Cinere, Depok! Yayasan Amal Khair Yasmin mempunyai sekolah SMP gratis berkualitas untuk orang miskin. Syaratnya: orang tuanya harus miskin. Banyak anak-anak mendaftar. Orang tuanya juga datang dan mengaku miskin. SMP gratis pun langsung penuh pendaftar baru dari “orang-orang miskin”. Tapi betulkah mereka miskin? Setelah diteliti, ternyata mereka bukan orang miskin. Bahkan ada yang punya mobil, mobilnya disembunyikan, lalu mengaku miskin agar anaknya bisa diterima di SMP gratis berkualitas itu. Kenapa seperti itu? Sekali lagi, inilah mindset! Mindset korupsi.
Dari gambaran itu, bagaimana kita melihat pemerataan pendidikan? Mungkin kasus ini bisa dilihat dari empat kategori. Pertama, soal mindset. Dari pada sekolah membuang-buang uang lebih baik disuruh mencari uang (kasus di desa-desa dekat Pelabuhan ratu). Kedua, orang tua lebih sayang uang ketimbang pendidikan (kasus Cinere, Depok). Penyebab pertama dan kedua itu dampaknya sama: banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah.
Ini berbeda dengan fenomena di Kabupaten Gunung Kidul. Di desa-desa terpencil di Semanu, Rongkop, dan Ponjong nyaris semua anak sekolah, meski kondisi orang tuanya miskin. Dengan berbagai upaya, orang tua mengharuskan anak-anaknya sekolah. Tidak hanya tamat SD, SMP, SMA tapi bila perlu sampai perguruan tinggi. Berbagai upaya dilakukan agar anaknya bisa mendapat pendidikan tingi. Ada yang mejual sapi dan tanahnya. Padahal sapi dan tanah itu adalah “mesin uang” keluarga. Tapi demi sekolah, apa pun dilakukan. Istilah mereka – seandainya kulit badannya harus dikelupas, orang tua sipa melakukannya demi sekolah anak. Dampaknya, desa-desa di Gunung Kidul yang dulu terkenal miskin dan kering kini tumbuh menjadi desa-desa yang makmur. Warga desanya pinter dan mampu memanfaatkan tanah-tanah kering dan tandus menjadi tanah produktif.
Baru-baru ini Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan 30% gedung sekolah di Jakarta tidak layak huni! Padahal anggaran Pemda DKI sekitar Rp 80 Triliun. Untuk apa anggaran sebesar itu? Jelas bukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Fenomena DKI itu, mungkin terjadi di provinsi-provinsi lain. Penyebabnya, lagi-lagi soal mindset: untuk apa membangun pendidikan yang hasilnya lama baru dipetik. Lebih baik uang itu untuk membangun gedung pemerintah, membangun pasar, membangun jalan, dan membangun infrastruktur fisik yang lain. Hasilnya cepat dirasakan. Ini beda dengan membangun SDM melalui pendidikan. Lama baru bisa dirasakan!
Pemabngunan SDM melalui pendidikan adalah keharusan jika ingin melihat kemajuan bangsa dan negara. Tanpa pendidikan berkualitas dan menjangkau semua rakyat, cita-cita memajukan bangsa dan negara tak akan tercapai.
Benar, Indonesia adalah negara kepualauan sehingga pemerataan pendidikan sulit dicapai. Oke. Kita lihat di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan ibu kota. Di daerah-daerah terpencil di Kabupaten Bogor dan Sukabumi, misalnya, orang dengan gampang menemukan sekolah-sekolah yang kondisi gedungnya memprihatinkan. Gurunya pun nyaris tak ada. Kadang hanya satu orang untuk satu sekolah. Kenapa terjadi? Lagi-lagi ini soal mindset. Kali ini mindset Pemda setempat yang abai dengan dunia pendidikan. Di Kabupaten Bekasi, misalnya, dana untuk perjalanan dinas menghabiskan hampir 20 persen APBD. Padahal, bangunam SD dan SMP yang nyaris roboh mencapai 40 persen dari banguna sekolah yang ada.
Bagaimana dengan guru negeri? Pemerintah memberikan “bonus” sertfikasi sebesar gaji pokok. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas guru. Faktanya, uang sertifikasi itu kebanyakan menjadi motor dan mobil baru. Kredit lagi. Jadi, secara keseluruhan sistem pendidikan kita terabaikan!
Bandingkan misalnya dengan pendidikan di Finlandia, negeri kecil di Skandinavia yang wilayahnya banyak danau dan hutan pinus. Negeri ini punya kepedualian besar terhadap pendidikan. Semua anak harus sekolah. Sekolah swasta dan negeri dibiayai negara. Tokh murid-muridnya sama, warga negara Finlandia. Semua gedung sekolah, apakah itu di kota maupun di pelosok desa, kualitasnya sama. Guru-gurunya juga berkualitas sama dengan jumlah yang mencukupi. Untuk guru di wilayah terpencil, ada tunjangan khusus. Walhasil, kualitas pendidikan pun merata.
Kenapa terjadi? Karena pemerintah dan penduduknya punya kesadaran tinggi bahwa pendidikanlah yang menjadi tiang utama untuk kemajuan bangsa. SDM berkualitas hanya bisa diperoleh dari pendidikan berkualitas!
Pemerintah harusnya sadar bahwa anaka-anak yang sekolah di negeri maupun swasta sama-sama orang Indonesia. Mereka adalah anak bangsa. Kenapa tidak diperlakukan sama? Guru-gurunya juga, swasta atau negeri, juga mendidik anak-anak bangsa. Kenapa reward-nya tidak disamakan! ss