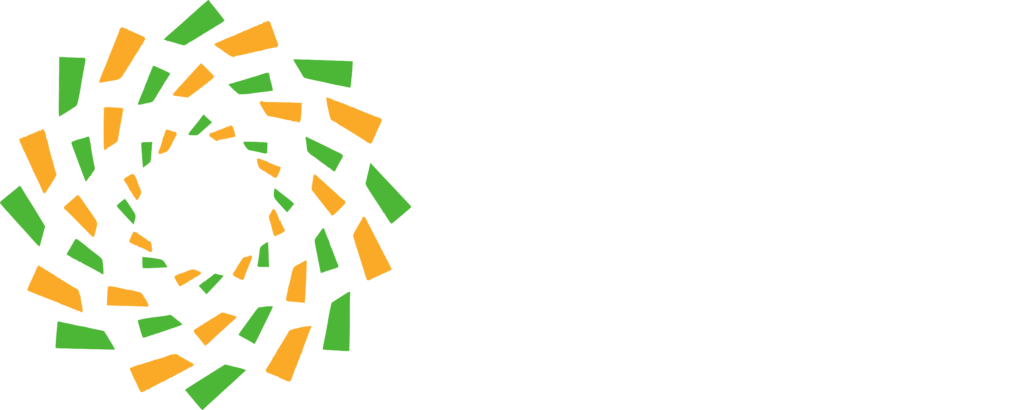Puasa, Ibadah Universal dan Kultural

Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa (QS. Al Baqarah [2]: 183). .
Ayat Alqur’an di atas menunjukkan puasa diwajibkan untuk orang beriman. Termasuk orang-orang beriman sebelum kamu. Penggalan ayat ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang sangat penting sehingga berlaku secara universal. Tak hanya umat Islam yang diwajibkan Allah untuk berpuasa, tapi juga umat beriman lain. Hanya saja mungkin metode dan waktu puasanya yang berbeda. Orang Jawa zaman dulu sebelum Islam datang ke Pulau Jawa, mengenal istilah pantang. Laku pantang ini menyerupai puasa. Orang Nashrani juga berpuasa pada har-hari tertentu. Begitu pula orang Yahudi, orang Hindu, dan orang Budha. Meski cara puasanya berbeda dengan umat Islam, tapi filosofinya sama. Melatih kesabaran, kedisiplinan, dan keataatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itulah sebabnya, Housen Nasr menyatakan puasa adalah ibadah universal yang sudah ada jauh sebelum Islam hadir. Kedatangan Islam mengukuhkan ibadah puasa dalam sebuah institusi religi yang diistimewakan Tuhan, bernama Bulan Ramadhan.
Ibadah puasa yang menjadi wilayah privat bagi mereka yang menjalankannya, dari tahun ke tahun telah menjadi kultur baru pada wilayah publik. Di Indonesia, misalnya, Bulan Ramadhan hadir dengan “spesifkasi kultural” yang berbeda dibanding bulan-bulan lainnya. Bulan Puasa berhasil mentransendensikan kebudayaan yang profan menjadi kebudayaan yang spiritual. Tarling (terawih keliling) dan bukber (buka bersama), misalnya, di Indonesia telah menjadi kosa kata baru yang “istimewanya” mengikat tokoh masyarakat dan pejabat publik untuk melaksanakannya. Tidak banyak kosa kata baru dalam bahasa Indonesia yang terus menguat eksistensinya di ranah publik seperti tarling dan bukber. Tiap bulan puasa kata tarling dan bukber mendapat otorisasi yang aplikatif di ranah publik. Bukber di rumah Megawati Soekarnoputri dalam rangka khaul Taufiek Kiemas, Rabu (8/6) lalu, misalnya, berhasil mempertemukan elemen-elemen politik dan budaya yang selama ini berserakan dan saling bersebrangan. Dengan demikian kata “bukber” mengalami pengayaan makna dan proliferasi ide. Bukber tidak sekadar menjadi perwujudan niat berbagi makan dan minuman, tapi juga melapangkan jalan untuk silaturahmi budaya. Ini berbeda misalnya dengan kata waskat (pengawasan melekat) yang pernah populer di zaman Orde Baru. Kata waskat yang digagas Ginanjar Kartasasmita di era Orde Baru ini, lambat laun hilang otoritas maknanya. Publik mungkin masih ingat arti dari kata waskat, tapi maka rilnya telah mengalami deteriorisasi, mengalami penuruan kualitas, dan pembusukan.
Dalam konteks inilah, Bulan Ramadhan memberikan sumbangan kultural terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang bhineka. Puasa pada bulan Ramadhan menjadi agenda spiritualitas nasional yang berbasis pada religio-kultural. Inilah makna kebudayaan dari ibadah puasa di Indonesia. Itulah sebabnya, para pemilik resto dan cafe dengan kesadaran sendiri, misalnya, menutup “bisnis”nya selama bulan puasa. Ini bukan sekadar menghormati umat Islam yang berpuasa. Tapi sudah mrenjadi kesadaran kultural, di mana puasa individual telah mengalami asosiasi kultural sebagai puasa nasional.
Puasa esensinya adalah self control atau pengendalian diri. Dalam Islam, mekanismenya secara visual dilakukan dengan tidak makan dan minum untuk periode tertentu, dari waktu Imsak sampai Magrib. Periodisasi self control secara fisik tersebut sebetulnya hanya simbol dari perintah Tuhan kepada manusia untuk melakukan self control secara menyeluruh dan sepanjang hidup. Dan itulah esensi puasa yang seharusnya kita sadari. Bukan puasa superfisial yang dampaknya hanya mengakibatkan rasa haus dan lapar, tapi puasa yang menuju transformasi budaya adiluhung untuk menuju kehidupan yang lebih ramah dan rahmah.