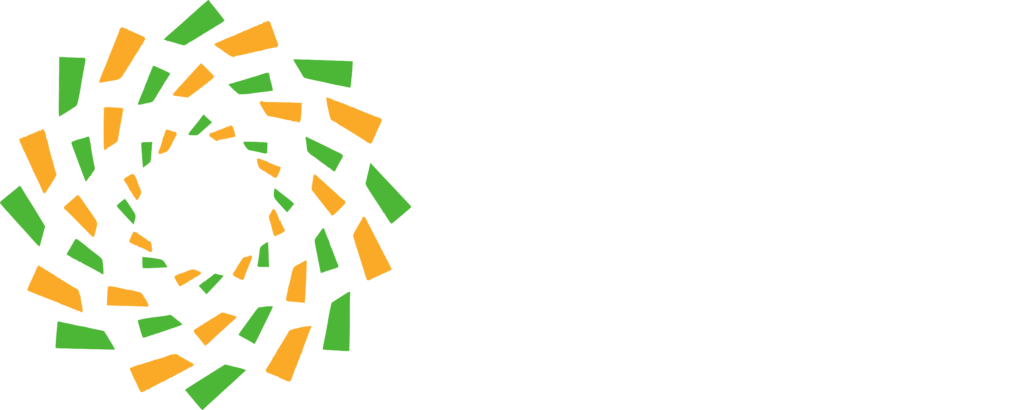Bila Anak TK Diminta membuat Kalimat dengan Kata Bom

Seorang guru menyuruh anak-anak didiknya untuk membuat kalimat dengan kata bom. Hasilnya: “Budi melemparkan bom ke pasar,” tulis seorang anak. Tak mungkinlah jika anak membuat kalimat seperti ini: Budi memakan bom! Ini artinya, kata bom jika dibuat dalam rangkaian kalimat, niscaya berujung pada makna “kekerasan” . Tanpa disadari, kata bom yang bermakna kekerasan itu, kemudian jadi “makanan otak” anak-anak. Apa yang terjadi kelak bila sejak kecil otak anak-anak disuguhi “makanan” kekerasan?
Gerakan Pemuda Anshar beberapa hari lalu menemukan buku pelajaran membaca berjudul “Anak Islam Suka Membaca” yang isinya mengenalkan narasi-narasi berbau kekerasan dan radikalisme di taman kanak-kanak (TK) Baiturahman, Cilodong, Depok. Dalam buku itu, anak-anak TK diperkenalkan dengan kalimat yang suku kata-katanya terdiri dari ‘gelora hati ke Saudi’, ‘bom’, ‘sahid di medan jihad’, ‘selesai raih bantai Kiai’. Kemudian ada juga kalimat dan kata-kata ‘rela mati bela agama’, ‘gegana ada di mana’, ‘bila agama kita dihina kita tiada rela’, ‘basoka dibawa lari’, dan ‘kenapa fobi pada agama’. Buku “Anak Islam Suka Membaca” ini karangan Murani Musta’in, istri dari Ayip Syafruddin, pimpinan kelompok Laskar Jihad di Solo. Penerbitnya Pustaka Amanah alamatnya di Jalan Cakra No. 30 Kauman, Solo.
Setelah informasi adanya buku ajar yang memperkenalkan istilah-istilah terorisme dan radikalisme ini menyebar di media cetak dan media digital, pemerintah (Kemendikbud) langsung bereaksi dan berjanji akan menarik buku tersebut. Yang jadi masalah, buku ini sudah beredar sejak tahun 1999 dan sudah cetak ulang 167 kali. Sejak heboh buku ajar teroris ini, konon, yang bisa ditarik baru 175 eksemplar. Bisa terbayang, berapa ribu eksemplar yang sudah beredar? Seandainya tiap kali cetak 3000 eksemplar, berarti selama 16 tahun ini, telah dicetak 167 x 3000 atau 501.000 eksemplar buku. Seandainya satu buku dibaca 5 anak, maka “pelajaran dari buku tersebut” telah masuk ke dalam otak 2.505.000 anak. Buku ini mulai beredar tahun 1999, berarti anak yang pertama kali mendapat pelajaran “terorisme” sekarang sudah berumur 21 tahun. Jika tahun 1999 cetak ulang 10 kali saja (dengan asumsi 167 kali cetakan selama 16 tahun), berarti saat ini, sudah ada 30.000 pemuda berusia 21 tahun yang “otak”nya sudah “terisi” makanan berbumbu terorisme dan radikalisme. Ini sangat mencemaskan kita semua.
Dalam otak manusia, terdapat banyak struktur dan sirkuit neurologis rumit yang menjadi suatu objek kajian dari ilmu yang dinamakan neurosains. Ketika fokus neurosains ditujukan pada relasi antara aktivitas sirkuit-sirkuit neurologis dalam otak dan perilaku beragama, muncullah sebuah disiplin ilmu yang dinamakan neuroteologi. Menurut neuroteologi, perilaku beragama anti-rasionalis fundamentalis ditimbulkan oleh aktivitas neurologis sangat kuat pada sirkuit amygdala yang menjadi suatu bagian neurologis dari sistim limbik otak manusia. Sebaliknya, perilaku beragama rasionalis ditimbulkan oleh aktivitas yang kuat pada sirkuit frontal lobes dalam organ otak manusia. Jika sirkuit frontal lobes diaktifkan bersamaan dengan sirkuit anterior cingulate, maka orang akan dapat beragama rasionalis sekaligus memiliki cinta, bela rasa dan empati yang tinggi terhadap kehidupan sesama. Jika orang terlibat terus-menerus dalam kegiatan keagamaan yang terfokus pada kemarahan dan rasa takut yang mengaktifkan organ amygdala, seperti terjadi pada kalangan beragama fundamentalis, anterior cingulate akan mengalami kerusakan permanen. Jika hal ini terjadi, seorang fundamentalis religius akan kehilangan kepedulian pada orang lain dan akan menyerang orang lain dengan agresif.
Jika anda mengharapkan suatu kejadian negatif di masa depan yang mengancam nyawa banyak orang, maka aktivitas di anterior cingulate akan menurun dan sebaliknya aktivitas di amygdala meningkat. Keadaan neurologis semacam ini menimbulkan kecemasan dan neurotisisme sangat tinggi. Orang yang menderita keadaan mental semacam ini akan tertarik pada agama-agama fundamentalis karena agama-agama jenis ini menawarkan suatu sistem kepercayaan religius yang sangat terstruktur yang mengurangi perasaan serba tidak pasti, dan yang memungkinkannya untuk menyalurkan semua dorongan agresif yang dibangkitkan oleh amygdala. Memakai sebuah metafora, kita dapat mengibaratkan bahwa ada dua ‘binatang’ dalam otak manusia, yakni ‘binatang jahat’ berupa amygdala dalam sistim limbik, dan ‘binatang baik’ berupa sirkuit frontal lobes dan sirkuit anterior cingulate. Mana dari ‘kedua binatang’ ini yang akan makin tumbuh besar, bergantung pada ‘binatang mana’ yang anda beri makan paling banyak, melalui lingkungan pergaulan anda, melalui pendidikan yang anda terima, melalui buku-buku yang anda baca, dan melalui pelatihan spiritual yang anda jalani.
Nah, dalam kasus buku ajar membaca untuk TK tersebut – kita bisa membayangkan bagaimana “perilaku” mereka di masa datang bila dikaitkan dengan proses yang terjadi pada otak mereka. Anak-anak sejak usia dini sudah diberi makan dengan materi-materi ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme sehingga yang berkembang adalah amygdala dalam sistim limbik yang merusak otak itu. Ini artinya, potensi anak-anak tersebut menjadi teroris besar sekali karena otaknya sudah terbiasa makan zat-zat yang mengandung terorisme dan radikalisme” (Iones Rakhmat, 2015).
Dari gambaran tersebut, dampak buku ajar terorisme di atas jelas luar biasa. Yang jadi persoalan, kenapa keberadaan buku ajar ini baru diketahui masyarakat setelah 16 tahun dipakai di taman kanak-kanak Islam di berbagai wilayah Indonesia? Sungguh naif! Apakah orang tua tak pernah memeriksa buku pelajaran TK anak-anaknya? Apakah guru-guru TK tidak mengetahui dampak dari bahan ajar tersebut. Lalu, ini yang terpenting, apakah pemerintah – dalam hal ini Kemendikbud dan Kemenag — tidak pernah memeriksa atau meneliti konten buku ajar di TK? Semoga ini menjadi pelajaran ke depan. Pemerintah hendaknya proaktif dalam menilai dan mengkaji buku-buku ajar di sekolah di seluruh wilayah Indonesia.