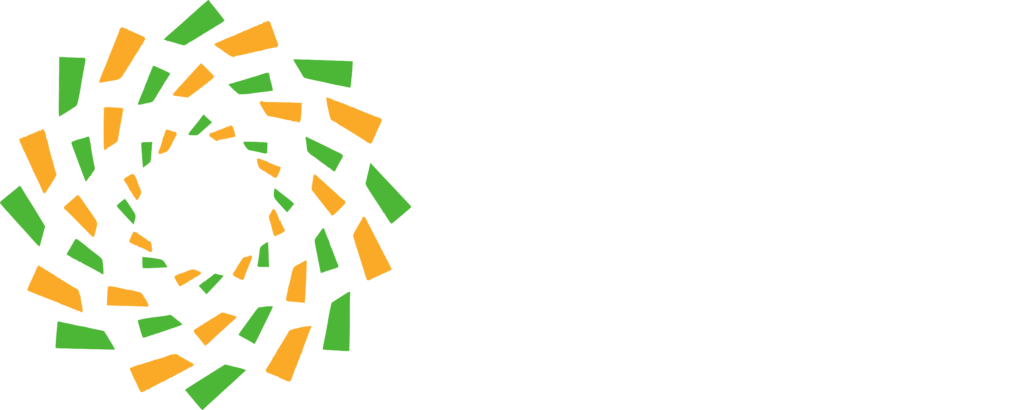Sebagai seorang jurnalis foto muda yang tinggal di Gaza , Fatima Hassouna tahu bahwa kematian selalu berada di depan pintunya. Selama 18 bulan terakhir ia mendokumentasikan serangan udara Israel atas Gaza: penghancuran rumahnya, pengungsian yang tak berkesudahan, dan pembunuhan 11 anggota keluarganya.
Pada suatu hari Rabu, beberapa hari sebelum pernikahannya, Hassouna yang berusia 25 tahun tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam rumahnya di Gaza utara. Sepuluh anggota keluarganya, termasuk saudara perempuannya yang sedang hamil, juga tewas. (“Jika Aku Mati, Aku Ingin Kematianku Bersuara Keras”, The Guardian, 18 Maret 2025).
Militer Israel mengatakan itu adalah serangan yang ditargetkan terhadap anggota Hamas yang terlibat dalam serangan terhadap tentara dan warga sipil Israel. Tapi, tak ada orang waras yang tak menduga bahwa Fatimah memang disasar secara khusus oleh Israel. Bukan hanya karena Fatimah memang terang-terangan berupaya membongkar kekejian rezim Netanyanhu Israel, tapi wajah sadis dan tak berperikamuniaan serangan Israel atas Gaza, selama lebih dari 1,5 tahun belakangan ini, sudah lebih dari cukup untuk menjadi dasar dugaan ini. Dan Fatimah bukanlah jurnalis pertama yang dibunuh Israel. Menurut catatan, Fatimah adalah korban terakhir dari pembunuhan tak kurang dari 170 jurnalis dan pekerja media di Gaza. Belum lagi para sukarelawan asing.
Tapi, sesuai belaka dengan harapan Fatimah, dia tidak tewas kecuali setelah karya-karyanya nya diketahui dunia, bahkan sebuah film dokumenter tentangnya – yang dibuat Sepideh Farsi, seorang produser Iran yang tinggal di Prancis – diputar di Festival Film Independen di Cannes.
Untuk menggambarkan betapa besarnya horor kita melihat kebiadaban ini, kata “speechless” mungkin adalah satu-satunya kata yang bisa diungkapkan, meski kata ini sesungguhnya hanya berarti tak ada kata apa pun yang bisa diungkapkan.Hanya kata-kata itu yang hari-hari ini melintas terus di kepala saya melihat fenomena pembantaian manusia di Gaza oleh para pembunuh berdarah dingin Zionis Israel.
Dan semua tulisan di atas dan di bawah ini hanyalah penjelasan atas satu kata itu. Speechless.
Kita tak usah lagi bicara tentang penyerbuan Hamas ke Israel yang dilakukan dalam hitungan beberapa jam dan, katakan, membunuh 1000 orang atau lebih. Diskusi, bahkan perdebatan, tentang legitimasi tindakan ini sudah panjang dilakukan. Dan, bahkan para pengutuk tindakan Hamas ini sekalipun, akan kehabisan kata-kata untuk bisa melegitimasi penghancuran dan pembantaian yang dilakukan Israel selama lebih dari satu tahun tanpa henti ini. Pembantaian ini telah memakan nyawa lebih dari 51 ribu orang, hampir semuanya mudah dipastikan adalah rakyat sipil. Dengan kata lain, bukan anggota Hamas yang adalah sayap militer Ikhwan di Gaza. Malah, nyaris separuhnya adalah anak-anak. Dan ini belum termasuk orang-orang yang dibuat cacat, anak-anak yang dibuat yatim-piatu, serta perataan dengan tanah berbagai fasilitas sipil vital – termasuk rumah sakit, gudang obat-obatan, fasilitas penyediaan air bersih, makanan, dll – yang dapat membunuh lebih banyak orang lagi.
Dan ini bukan hanya dilakukan secara terang-terangan, di depan mata dunia, nyaris tanpa upaya pencegahan berarti – termasuk oleh negara negara yang selama ini sebetulnya tidak (sepenuhnya) diam menentang agresi Israel dan genosida Israel ini. Bahkan kejahatan kemanusiaan terbesar paruh abad terakhir ini didukung oleh (pemerintah di) negara-negara terkuat, yang mendaku sebagai pilar peradaban dunia.
Bagi sebagian orang, tragedi besar ini bisa memaksa untuk bertanya, dimana Tuhan? Ya. Karena kekejaman tidak terperikan peperangan ini, dan kenyataan ketakberdayaan manusia, orang harus bertanya, di mana Tuhan? Suatu hal yang nyaris tak terelakkan.
Seperti Ivan dalam novel The Brothers Karamazov karya Fyodor Dostoyevsky, dalam kejadian ethnic cleansing di Gaza sekarang ini, orang dipaksa bertanya. Di mana Tuhan, di tengah kebuasaan manusia atas manusia ini? Kenapa dia membenarkan semua ini terjadi?
Tapi, sebelum itu, kita harus terlebih dulu bertanya, di mana manusia? Manusia yang, konon, bergelar khalifah (wakil) Tuhan itu? Pertama, yang kita lihat segera dalam pagelaran kekejaman ini adalah manusia-manusia yang, alih-alih menjadi khalifah Tuhan dalam menata bumi ini, adalah manusia-manusia yang lebih sadis dari binatang buas. Jauh lebih sadis. Bahkan, binatang buas pun merupakan pembanding yang terlalu baik bagi jenis manusia-manusia yang menjadi dalang kejahatan kemanusiaan ini.
Kedua, kalau memang benar manusia memiliki potensi untuk menjadi khalifah Tuhan, apakah potensi ini benar-benar bisa teraktualkan? Kalau jawabannya bisa, di manakah manusia-manusia ini? Dalam sejarah, kalau pun ada, jumlah manusia seperti ini terlalu sedikit. Sehingga, yang lebih mungkin adalah yakin bahwa pada dasarnya manusia itu memang jahat dan buas.
Maka tidak salah jika tak sedikit ahli mengasosiasikan gejala meluasnya ketidakbertuhanan orang-orang Eropa modern kepada fakta kekejaman PD I dan II yang melanda negara-negara di wilayah ini, yang berakibat banyak di antara mereka menutup ruang bagi keberadaan Tuhan. Alhasil… Pembantaian manusia, termasuk anak-anak tak berdosa di, depan mata dunia dengan kekejaman yang tak terbayangkan bahkan oleh imajinasi kita yang paling liar sekalipun, ini bukan hanya melenyapkan nyawa banyak orang, tapi bisa juga melenyapkan keyakinan orang pada kemanusiaan, dan keimanan kepada keberadaan Tuhan.
Seperti kata Ivan Karamazov kepada Alyosha, adiknya: “Bukan Tuhanlah yang tak aku terima, pahamilah, tapi dunia ciptaan Tuhan ini yang tak bisa kuterima, yang aku tak bisa setuju untuk menerimanya.”
Maka – setiap manusia yang masih memiliki keyakinan kepada kemanusiaan manusia, serta keimanan kepada keberadaan Tuhan – tak boleh tinggal diam. Karena sesungguhnya yang dibunuh adalah (ke-)manusia(-an) secara keseluruhan. Dan di atas segalanya, diamnya kita sesungguhnya secara pelan-pelan telah membunuh Tuhan – kalau saja kita beriman. Membunuh keimanan orang akan kemahakuasaan dan kewelasasihan-Nya.
Padahal, apa lagi daya tarik keberadaan Tuhan kalau bukan bahwa dia Mahakuasa dan Mahawelasasih? “Bukan Tuhan yang tak bisa kuterima, Alyosha. Hanya saja, dengan segala hormat, kukembalikan tiket ini kepadanya.”
Dan, sebelum itu, kita dituntut untuk melakukan apa saja yang kita bisa, sesedikit atau sebanyak apa pun, untuk melawan kekejaman dan kejahatan kemanusiaan ini. Kalau kita mau menjadi pembela Tuhan, maka hal itu . tidak boleh kita lakukan dengan mengafirkan manusia yang tak sekeyakinan dengan kita, atau memusuhinya, atau bahkan membunuhinya. Melainkan justru dengan membela manusia-manusia tertindas dari kelompok apa pun: siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.
Seperti Fatimah Hassouna, kita mesti bersuara keras. Kalau tidak melalui kematian kita, setidaknya melalui ke-“hidup”-an kita…
Haidar Bagir